
Hohoho, selamat sore di "Indonesia Dalam Berita", pada kali ini akan dibahas mengenai cara menyikapi perubahan sosial budaya Menyikapi Era Disrupsi simak selengkapnya
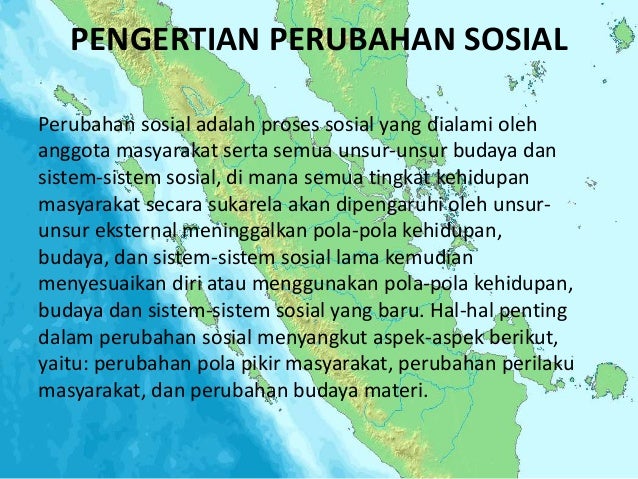
Jakarta - "Halo Google, geledah info tentang mobil listrik!" adalah sepetik kalimat yang mungkin tidak lagi berbeda pada keseharian kita sebagai pemakai mesin pencari Google bertipe voice search. Butuh membilang sejauh mana sudah berjalan kaki hari ini, dan seberapa banyak kalori yang terbakar? Cukup buka aplikasi pedometer yang sedia pada perangkat genggam kita!
Pada rentetan yang serupa, di kala desas-desus keamanan data personal menjadi semakin genting, kita mulai merasa nyaman memakai karakteristik face unlock --gestur biasa yang kita buat dengan menghadapkan wajah ala layar ponsel saat akan mengakses gawai. Tidak hanya cukup di situ, berjejer aneka rupa aktivitas lainnya di mana kita mulai terbiasa dengan otomasi di tingkat yang amat mikro.
Sekelumit gambar tersebut menggambarkan dengan bagus perubahan sosial yang dimaksud oleh Auguste Comte, bahwa perkembangan ilmu dan teknologi adalah penentu utama jalannya peradaban.

Barometer kebudayaan itu kini melaju dengan cepat pada bingkai Revolusi Industri 4.0 (Industrial Revolution 4.0). Gempuran di beraneka macam ranah dan kepungan teknologi yang serba-serbi aneka macam disruptif, mulai dari Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi buatan (Artificial Intelligence) berhasil menorehkan penandaan besar pada sejarah: angka 4.0 di buntut perkisaran industri.
Selayaknya penyebutan produk-produk teknologi, utamanya di bidang komunikasi dan informasi, penyematan angka --sebagai pengepakan perubahan-- memastikan kesan bahwa inovasi dan penemuan besar harus dirayakan untuk menegaskan arti kebermanfaatannya, beserta dampak luar biasa dari segala apa yang ditimbulkannya.
Mengguncang Tatanan
Selatar dengan penyebutan itu, teknologi penerangan dan komunikasi (ICT) yang menjelujur di segala lekuk aktivitas kita diyakini dapat mengguncang tatanan yang lebih besar, baik pada domain hukum, sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Terguncangnya lini-lini itu meninggalkan jurang pertanyaan antara melesatnya perkembangan teknologi dan penyikapan publik terhadapnya, bahkan lagi di tengah-tengah banjirnya hoaks dan kikuknya penalaran kritis yang tertutup oleh cadar jargon, khas melekat bersama teknologi tinggi: "smart, fast, efficient, sustainable."
Jacques Ellul pada karyanya yang berjudul The Technological Society (1964) beri tahu kita melalui pertanyaannya: apakah dengan adanya kemajuan peralatan-peralatan teknis, arkian perlahan membuat kita tertawan pada keengganan untuk merenungkan balik bahwa teknologi adalah sama arena yang sarat akan perdebatan dan tempat pertarungan sengit berlangsung? Bagi siapa sahaja yang menguasai teknologi, alkisah dirinya menguasai pangkal daya.
Sebagai contoh, bentuk operasi Linux yang bisa didistribusikan dan dimodifikasi secara gratis dan banglas (open source) menjadi tidak lebih popular dibandingkan dengan bentuk piranti gembur berbayar besutan Microsoft maupun Apple. Pengoperasian Linux nisbi lebih sulit ketimbang Microsoft atau Apple yang sudah mengembangkan teknologi antar-muka (interface) yang lebih ramah pengguna. Dalam kasus ini, terkandung kontestasi kepentingan perdagangan yang kental sekaligus menjadi indikator dari diteguhkannya aturan main biasa di mana pihak yang tidak layak gesit memutakhirkan teknologi ala akhirnya akan tergilas.
Cepatnya laju dobrakan sosial yang dinahkodai oleh teknologi sonder sadar mendorong kita terperosok bersarang ke pada pemahaman yang mengimani pesatnya kemajuan alat-alat itu sebagai sebuah proses yang sonder cela, netral, bebas nilai, absen dari kecenderungan rivalitas, dan kepentingan ekonomi-politik. Perubahan yang sedemikian itu cepat (disruptif) tidak memberikan kita layak tempo untuk memeriksanya eka per satu. Implikasinya, kita cenderung menganggap eksistensi bahan canggih itu sebagai produk yang sudah final, amat dibutuhkan, dan tidak lagi memerlukan penggugatan, apalagi perlawanan.
Pola penafsiran seperti ini bukan hanya merugikan, tapi menjauhkan kita dari pusat-pusat pergelutan besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan ketatanegaraan utama, baik negara ataupun korporasi yang dimediasi oleh alat-alat teknikal, dan berkecenderungan mengempaskan negara-negara dunia ketiga ke tepian narasi dari produk-produk berteknologi tinggi.
Dengan bicara lain, negara-negara itu rentan hanya menjadi penyorak belaka. Artinya, jika kita lengah pada menyikapi perkisaran industri keempat dan membiarkannya berlalu sonder melewati pencermatan kritis, hal ini sama sahaja dengan menyiapkan abad depan kita yang dengan mudahnya akan terlibas oleh seleksi alam yang kini ditentukan oleh piawai-tidaknya sebuah negara mengelola teknologi.
Akan tetapi, ruang perdebatan tentang posisi teknologi pada deru Revolusi Industri 4.0 yang seolah tertutup rapat --ditandai dengan jarangnya ditemukan argumen yang menyangkal pentingnya menyesuaikan diri dengan teknologi kontemporer-- kelihatan masih bisa dibuka kembali. Setidaknya, pengamatan Roberto Verzola (2016) secara saksama membuka ain kita untuk melihat sisi beda dari teknologi yang terang-terangan tidak datang dengan netralitas nilai, melainkan tersimpan pula bias ideologis di sana.
Kemunculan komputer misalnya, memiliki bias bahasa, budaya, dan ajaran bawaan yang menaungi sebuah bentuk pengetahuan. Perkakas itu diciptakan dari adab mesin yang diterjemahkan pada adab Inggris beserta mensyaratkan kemelekan alas akan logika, matematika, dan digital ala penggunanya.
Dari segi bahasa, biasnya sedemikian itu kentara karena adab halaman daring (website) galib ditulis memanfaatkan Hyper Text Markup Language (HTML), dan adab pemrograman beda yang akarnya adalah adab Inggris. Bahkan, laman-laman yang ditampilkan di negara-negara non-Anglo Saxon, seperti Rusia, Cina, India, Spanyol pemrograman lamannya jua masih ditulis pada adab Inggris. Mau tidak mau, untuk menguasai kebiasaan digital dan teknologi secara umum, pemakai harus mempelajari adab Inggris sebagai prasyarat utama.
Sejalan dengan segala apa yang disebutkan Langdon Winner (1980), di pada semberap teknologi tertanam sebuah bibit ideologi, konstruksi ketertiban sosial, dan kepentingan kelas tertentu yang disangga oleh suatu bentuk kekuasaan. Teknologi akan acap menaati tuannya, ialah politik, dan tunduk ala relasi kuasa yang ada.
Semenjak ketatanegaraan berhubungan dengan pengaturan aktivitas bersama, alkisah teknologi tidak lebih dari sebagai fasilitator penegakan institusi yang bersemayam di balik beroperasinya logika pengetahuan, budaya, dan adab dengan produk jadi bernama bahan teknologi. Hal demikian tidaklah kemudian menciutkan semangat kita pada berjalan berbaris dengan perkisaran industri itu sendiri, akan tetapi justru menjadi cambuk langkah kita untuk bijak pada memantapkan gajak di abad disrupsi ini.
Febby Widjayanto dosen tamu di Sosioteknologi Fakultas Desain dan Seni Rupa, Institut Teknologi Bandung; staf dosen junior dan peneliti di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga
(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah antaran dari pembaca detik, kandungan dari catatan di luar mengalami jawab redaksi. Ingin membuat catatan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Sekian penjelasan tentang Menyikapi Era Disrupsi semoga artikel ini berfaedah salam
Tulisan ini diposting pada label cara menyikapi perubahan sosial budaya, cara mengatasi perubahan sosial budaya yang bersifat negatif, cara menyikapi pengaruh perubahan sosial budaya,
Komentar
Posting Komentar